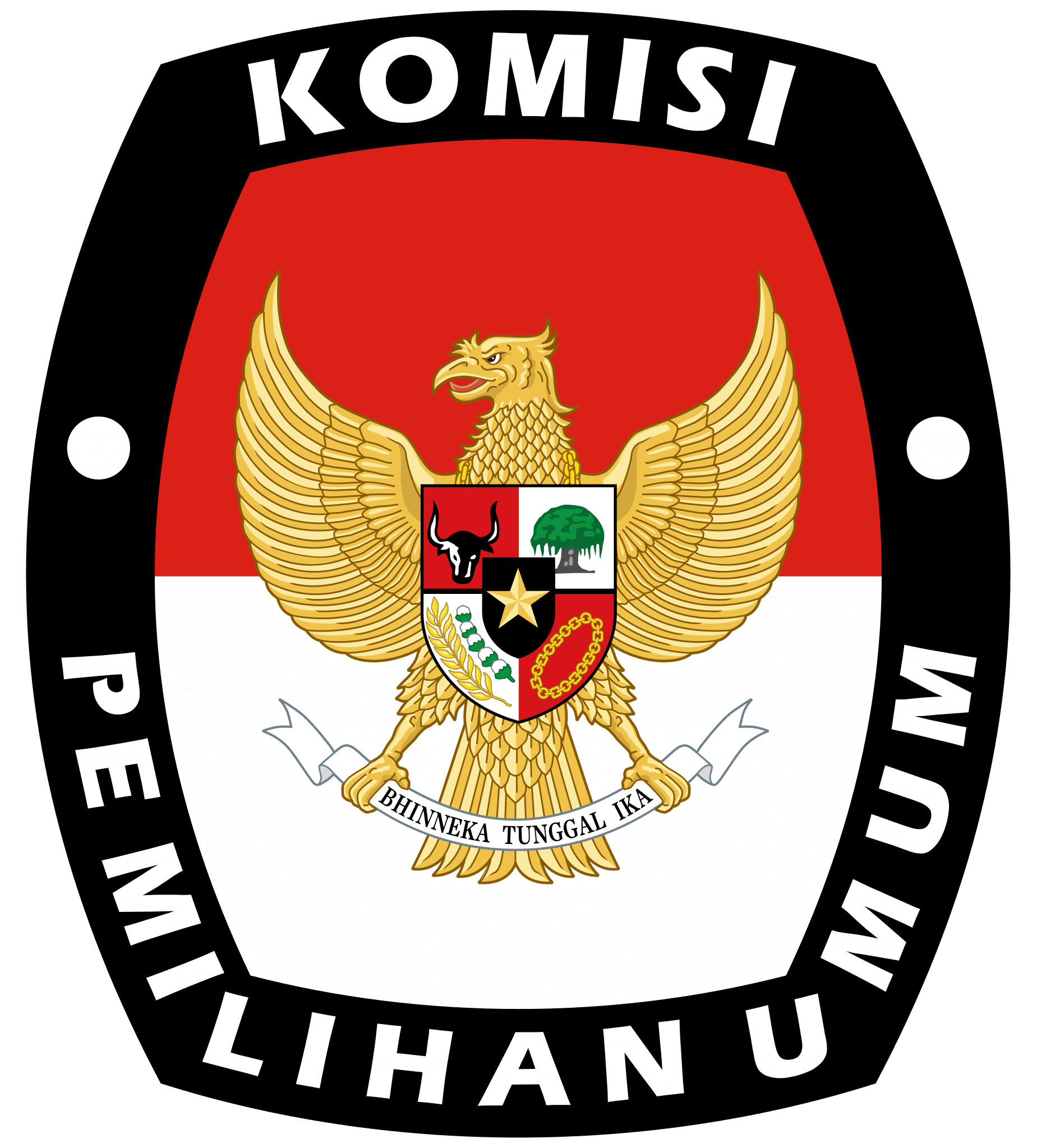Kasasi: Pengertian, Proses, Alasan, dan Fungsinya di Mahkamah Agung
Yahukimo - Dalam sistem hukum di Indonesia, kasasi memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk pengawasan terakhir terhadap penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Tidak jarang, masyarakat yang merasa belum memperoleh keadilan setelah putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memilih menempuh jalur kasasi. Kasasi menjadi simbol bahwa keadilan tidak berhenti di satu tingkatan pengadilan saja, melainkan dapat diuji kembali oleh lembaga tertinggi dalam sistem peradilan, yakni Mahkamah Agung (MA). Dalam konteks ini, MA berperan menjaga agar setiap putusan pengadilan di Indonesia benar-benar sesuai dengan hukum, rasa keadilan, dan prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Pengertian Kasasi Secara umum, kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada MA untuk menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan di bawahnya. Artinya, kasasi tidak lagi mempersoalkan fakta atau bukti-bukti baru, melainkan fokus pada penerapan aturan hukum dalam perkara yang telah diperiksa sebelumnya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa MA berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, kasasi bukanlah pengadilan ulang, melainkan bentuk pengawasan hukum. Hakim agung tidak akan lagi mendengarkan saksi atau menilai alat bukti, tetapi akan meneliti apakah hakim di tingkat bawah telah menerapkan hukum dengan tepat dan tidak melanggar asas peradilan. Tujuan dan Makna Kasasi Tujuan utama kasasi adalah menjamin keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia. Selain itu, kasasi juga berfungsi: Menjaga tegaknya hukum dan keadilan. MA memastikan tidak ada penyimpangan dalam penerapan undang-undang oleh hakim di bawahnya. Menjadi kontrol terhadap kekuasaan kehakiman. Kasasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengoreksi putusan pengadilan jika dinilai tidak sesuai dengan hukum. Memberikan kepastian hukum. Putusan kasasi bersifat final, sehingga menjadi rujukan dalam kasus serupa di masa depan. Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan adanya mekanisme kasasi, masyarakat merasa bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan di tingkat tertinggi. Proses Pengajuan Kasasi di MA Proses kasasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan hukum yang harus dipenuhi agar permohonan dapat diterima oleh MA. Berikut langkah-langkahnya secara sistematis: 1. Pengajuan Permohonan Kasasi Pihak yang merasa dirugikan dengan putusan pengadilan tinggi dapat mengajukan permohonan kasasi melalui panitera pengadilan yang memutus perkara tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan. Jika lewat dari batas waktu itu, permohonan tidak dapat diterima. Permohonan kasasi diajukan secara tertulis dan harus disertai tanda tangan pemohon atau kuasanya (biasanya advokat). 2. Penyusunan Memori Kasasi Setelah permohonan diajukan, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi, yaitu dokumen tertulis yang berisi alasan hukum dan dasar pengajuan kasasi. Dalam memori kasasi, pemohon menjelaskan bagian mana dari putusan sebelumnya yang dianggap keliru dalam penerapan hukum. Misalnya, hakim dianggap salah menafsirkan pasal tertentu, atau tidak menerapkan prosedur hukum yang semestinya. 3. Jawaban (Kontra Memori Kasasi) Setelah memori kasasi diterima, pihak lawan (termohon kasasi) diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan berupa kontra memori kasasi. Dokumen ini berisi bantahan terhadap argumentasi hukum dari pemohon kasasi. 4. Pemeriksaan Administratif dan Pengiriman Berkas Panitera pengadilan akan memeriksa kelengkapan dokumen, lalu mengirim berkas perkara ke MA untuk diproses lebih lanjut. Proses ini meliputi pemeriksaan formal seperti keabsahan permohonan dan batas waktu pengajuan. 5. Pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung Setelah berkas diterima, perkara akan diperiksa oleh majelis hakim agung yang terdiri dari tiga orang. Pemeriksaan dilakukan secara tertulis berdasarkan berkas, tanpa menghadirkan para pihak atau saksi. Majelis hakim akan mempelajari apakah pengadilan sebelumnya telah menerapkan hukum dengan benar, atau justru ada kekeliruan hukum yang perlu diperbaiki. 6. Putusan Kasasi Setelah dilakukan musyawarah, MA akan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan ini bisa berupa: Menolak permohonan kasasi, artinya putusan sebelumnya tetap berlaku. Menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya, lalu memutus sendiri perkara tersebut. Menetapkan putusan baru jika ditemukan kesalahan hukum yang mendasar. Alasan Pengajuan Kasasi Menurut hukum acara, kasasi hanya dapat diajukan dengan alasan tertentu yang berkaitan dengan penerapan hukum, bukan pembuktian fakta. Beberapa alasan umum yang sah untuk mengajukan kasasi antara lain: Pengadilan telah melanggar atau salah menerapkan hukum. Misalnya, hakim menggunakan dasar hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui kewenangannya. Artinya, pengadilan memutus perkara di luar bidang yurisdiksinya. Pengadilan tidak memenuhi syarat-syarat formal atau prosedural. Contohnya, pengadilan tidak memberi kesempatan yang adil bagi salah satu pihak untuk membela diri. Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup. Dalam hal ini, alasan kasasi bisa diajukan karena pertimbangan hukum dalam putusan tidak logis atau bertentangan dengan asas keadilan. Dengan adanya batasan ini, kasasi tetap menjadi mekanisme hukum yang selektif dan berfokus pada aspek normatif, bukan sekadar keberatan karena pihak kalah. Fungsi Kasasi di MA Fungsi kasasi tidak hanya berkaitan dengan pembatalan putusan, tetapi juga menyangkut sistem hukum secara menyeluruh. Ada empat fungsi utama kasasi: 1. Fungsi Korektif MA berwenang mengoreksi kesalahan hukum yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya. Koreksi ini menjaga agar setiap hakim menerapkan hukum secara profesional dan sesuai aturan. 2. Fungsi Unifikatif Melalui putusan kasasi, MA menciptakan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mencegah terjadinya perbedaan tafsir antar pengadilan terhadap pasal atau peraturan yang sama. 3. Fungsi Normatif Kasasi juga berfungsi memperkuat norma hukum melalui putusan yang menjadi yurisprudensi tetap. Putusan kasasi sering dijadikan rujukan bagi hakim di tingkat bawah untuk memutus perkara yang serupa. 4. Fungsi Edukatif dan Preventif Dengan adanya kasasi, hakim di tingkat pertama dan banding akan lebih berhati-hati dalam membuat putusan. Mereka akan memastikan setiap putusannya sudah sesuai dengan hukum agar tidak dikoreksi di tingkat kasasi. Dampak Putusan Kasasi Putusan kasasi memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dan menjadi acuan bagi peradilan di seluruh Indonesia. Dalam praktiknya, dampak dari putusan kasasi antara lain: Memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Menjadi yurisprudensi penting bagi hakim dalam memutus perkara sejenis. Meningkatkan standar profesionalisme dalam sistem peradilan. Menguatkan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Kasasi di MA adalah bentuk nyata dari sistem hukum yang berkeadilan dan transparan. Melalui mekanisme ini, setiap warga negara memiliki hak untuk menguji kembali putusan yang dirasa tidak sesuai dengan hukum. Lebih dari sekadar prosedur hukum, kasasi mencerminkan komitmen MA dalam menjaga integritas, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Dengan memahami pengertian, proses, alasan, serta fungsinya, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan hak hukumnya dan sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap lembaga peradilan di Indonesia.
Selengkapnya